Undang-undang Administrasi Pemerintahan: Quo Vadis Peradilan Tata Usaha Negara (Bagian 4)
Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara
Selain
penambahan kewenangan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pasca berlakunya
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat
pula perluasan kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara. Secara garis besar
perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara itu mencakup 2 hal pokok,
yakni yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan yang berkaitan
dengan upaya hukum sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan.
Merupakan
sebuah fakta notoir bagi kalangan
praktisi, bahwa eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sedemikian terbatasnya.
Tak hanya ruang lingkup kewenangannya, tapi juga faedah serta kepastian
penyelesaian (pelaksanaan putusan) hukum, yang menjadi tujuan akhir proses
peradilan, dirasakan masihlah jauh dari konsep ideal. Seperti yang pernah
diungkapkan Adriaan W. Bedner, bahwa: “Pada dasarnya pemerintah tidak menyukai
kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat bahwa hampir semua wakil rakyat
(waktu itu) menyadari bahwa pemerintah orde baru tidak akan bersedia menerima
campur tangan pengadilan dalam hal-hal yang langsung berkaitan dengan
pengendaliannya pada negara[1].
Salah
satu indikasinya menurut Umar Dhani adalah: “tidak ada dukungan dari penguasa dalam tataran implementatif, sehingga
apa yang menjadi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dalam tahap
pelaksanaannya tidak didukung oleh saran dan prasarana, sehingga penyelesaian
dari putusan pengadilan menjadi terabaikan[2]”.
Indikasi
normatif yang juga menunjukkan pembatasan itu adalah ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun
2004, yang secara jelas merefleksikan sesempit apa peranan Peradilan Tata Usaha
Negara dalam menegakkan supremasi hukum di negeri ini.
Undang-undang
Administrasi Pemerintahan, dapat dikatakan sebagai titik balik dari
keterbatasan peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakan Hukum
Administrasi. Asumsi itu tumbuh saat Undang-undang Administrasi Pemerintahan
memberikan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana menjadi
kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, yang selama ini cenderung
restriktif.
Namun
demikian, pemberlakukan ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan
tersebut, terutama ketentuan Pasal 87, tidak serta merta menghapus
kriteria-kriteria KTUN yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009,
melainkan mengalami revitalisasi[3].
Dengan
tidak adanya penegasan ketidakberlakukan terminologi serupa dalam Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara (terkhusus kriteria KTUN), maka menurut hemat
penulis, pengujian keabsahan KTUN di Peradilan Tata Usaha Negara bisa dilakukan
secara alternatif, dengan menggunakan dasar Undang-undang Peradilan Tata Usaha
Negara sendiri, ataupun dengan dasar Undang-undang Administrasi Pemerintahan.
1. Keputusan Berbentuk Elektronis
Sebagaimana diungkapkan
Indroharto, sebuah surat dikatakan keputusan tata usaha negara, penekanannya
berada pada sifat dan isi/substansi, bukan pada bentuk dari surat tersebut.
Jadi sepanjang memenuhi prasyarat sebagaimana Pasal 1 angka 3, dan terakhir
diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahu 2009, maka kendati
tidak berjudul “Keputusan”, maka surat tersebut telah memenuhi kriteria
keputusan tata usaha negara.
Dengan demikian, konsep yang
dibangun dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014,
sejalan dengan hal itu. Karena sejatinya, keberadaan suatu keputusan terletak
pada sifat serta isi/substansi dari surat tersebut, bukan pada bentuk maupun
wujud fisik berupa dokumen yang dicetak ataupun dokumen digital (tidak
dicetak), sepanjang telah jelas dan nyata apa yang diputuskan/diterangkan di
dalamnya, maa secara limitatif itu merupakan sebuah “beschikking”.
2. Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha
Negara
a. Mencakup tindakan faktual;
Pergeseran kewenangan menguji
tindakan faktual dari Peradilan Umum kepada Peradilan Tata Usaha Negara,
bukanlah hal yang mengherankan. Onrechtmatige
overheidsdaad
b. Keputusan TUN di lingkungan Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif dan penyelenggara negara lain;
Pemuatan norma ini secara tekstual,
merupakan penegasan dari konsep bahwa keputusan tata usaha negara bukan hanya
terbatas pada lingkup eksekutif saja. Sepanjang yang dilaksanakannya adalah
urusan pemerintahan, dalam arti bukan fungsi legislasi (pembuatan
perundang-undangan), maupun fungsi yudikasi (mengadili dan memutuskan perkara[4]), maka keputusan tersebut
termasuk kriteria keputusan tata usaha negara.
c. Berdasarkan perundang-undangan dan AUPB;
Karena sifat praesumptio justae causa, maka seburuk
apapun sebuah keputusan administrasi tetap dianggap sah dan berlaku, selama
belum dinyatakan sebaliknya. Sehingga dengan analogi terhadapnya, semua
keputusan administrasi secara filosofis harus dianggap telah diterbitkan
berdasarkan perundang-undangan AUPB, sepanjang belum dinyatakan sebaliknya.
d. Final dalam arti luas;
Dalam penjelasan Pasal 87
huruf d Undang-undang Administrasi Pemerintahan, dikatakan bahwa final dalam
arti luas diartikan mencakup keputusan yang diambilalih oleh atas pejabat yang
berwenang.
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan
akibat hukum;
Dapat ditafsirkan bahwa
ketentuan ini lebih bersifat visioner, yakni mengasumsikan adanya potensi
akibat hukum dari keputusan yang terbit. Misalnya, A mempersoalkan pengumuman
data yuridis BPN, karena lokasi tanah tumpang tindih dengan tanah yg diklaim
miliknya.
f.
Keputusan
yang berlaku bagi warga masyarakat.
Kendati rumusan yang dipakai
adalah “berlaku bagi masyarakat”, tapi secara limitatif hal ini hanya terbatas
pada “beschikking” saja, yakni
berlaku pada orang tertentu, golongan tertentu atau kelompok masyarakat
tertentu. Sehingga misalnya, walaupun Peraturan Daerah juga memiliki kekuatan
imperatif terhadap warga masyarakat, namun karena itu bersifat “regeling”, maka tidak termasuk katagori
Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Sifat Fiktif Positif
Hal ini bisa disebut sebagai langkah
progresif, implementasi dari pergeseran konsep administrastur pemerintahan yang
mengatur (regulatory function),
menjadi administratur pemerintahan yang melayani (service function), dan hakikatnya itu tak lain juga merupakan
pergeseran paradigma dari negara hukum menjadi negara kesejahteraan.
Kontradiktif dengan ketentuan
Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dalam Pasal 53 ayat (3)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015 tegas dinyatakan bahwa tidak ditetapkannya
atau tidak dilakukannya (sikap diamnya) Badan/Pejabat Pemerintahan, terhadap
permohonan yang diajukan, maka dianggap dikabulkan secara hukum.
Namun demikian, terhadap sikap
diamnya tersebut tetap harus menempuh proses pengadilan untuk mendapatkan
putusan penerimaan permohonan[5]. Pemeriksaan pengadilan
dalam permohonan ini, diasumsikan sama/serupa dengan pemeriksaan pengadilan
dalam hal permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang (vide Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014), sebagaimana
dijelaskan sebelumnya. Karena pada keduanya, tidak terdapat obyek sengketa
definitif (berupa sebuah keputusan tata usaha negara, bahkan tindakan tata
usaha negara), melainkan lebih bersifat pemeriksaan normatif terhadap permohonan
yang diajukan[6],
yang secara konseptual semestinya tidak jauh berbeda dengan sifat pemeriksaan
PUU di Mahkamah Konstitusi.
III.
4. Ambiguitas & Pertentangan Norma tentang Kewenangan Mengadili
Kaidah
upaya administrasi ditemukan tak hanya dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha
Negara tapi juga dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Ini termuat
dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa: “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima
atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan”
Klausula
tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan kritis, apakah kata “dapat” itu
merepresentasikan kaidah imperatif (keharusan) ataukah kaidah alternatif
(pilihan)? Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal Pasal 76 ayat (3) Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 itu secara filosofis mungkin meniru kata “dapat” dalam
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang diartikan
bahwa orang/badan hukum perdata, boleh menggugat, boleh juga tidak menggugat.
Namun
konteks “dapat” di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 itu kurang pas bila diterapkan dalam kaidah upaya administratif,
sebab kata “dapat” di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
lebih merupakan pilihan tindakan hukum (bersifat alternatif), sedangkan kata
“dapat” di dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan[7] maupun Pasal 76 ayat (3)
Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan kaidah prosedural yang harus ditempuh
(bersifat imperatif)[8].
Potensi
pertentangan norma muncul saat Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi
Pemerintahan dikonfrontasikan dengan ketentuan pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab bila
makna “Pengadilan” dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi
Pemerintahan tersebut diacukan kepada Pasal 1 angka 18 Undang-undang
Administrasi Pemerintahan, maka akan terjadi ambiguitas makna serta kompetensi
absolut antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara[9].
Terkait
hal ini, mungkin saja ada yang berpendapat bahwa asas hukum umum bisa
diterapkan, yakni asas lex speciali derogate legi generali ataupun
asas lex posteriori derogate legi priori. Namun tepatkah memperbandingkan
kekhususan/keumuman Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan
Undang-undang Administrasi Pemerintahan, atau memperbandingkan
kebaruan/kelampauan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan
Undang-undang Administrasi Pemerintahan[10]?
Mataram, 18 Agustus 2015
Mataram, 18 Agustus 2015
[1]
Adriaan W. Bedner, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia
(Sebuah Studi Sosio-Legal), Jakarta: Huma, 2010, hlm. 68.
[2]
Umar Dhani, Putusan Pengadilan Non-Executable. Proses dan Dinamika Dalam Konteks
PTUN, Yogyakarta: Genta Press, 2015, hlm. 3
[3] Lihat: Slamet Suparjoto, op.cit. hlm. 67
[4]
Namun perlu dikaji bahwa saat ini,
fungsi -yang serupa dengan fungsi- yudikasi tak hanya menjadi domain Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konsitusi selaku pemegang Kekuasaan Kehakiman saja. Lembaga
semisal KPPU, DKPP atau Komisi Informasi Pusat/Daerah, dipersepsikan memiliki
fungsi yudikasi juga.
[5] Lihat ketentuan Pasal 53 ayat (4), (5),
dan (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.
[6]
Bisa diperbandingkan juga dengan
sistem pemeriksaan akusator dan inkuisitor dalam Hukum Pidana. Dimana dalam
sistem akusator, para pihak diposisikan setara dan sama-sama menjadi subyek
pemeriksaan, sementara dalam sisten inkuisitor, para pihak diposisikan sebagai
obyek pemeriksaan.
[7]
Meski tekstualnya berbunyi:
“dapat” namun sifat imperatif-nya disini adalah ketentuan Pasal selanjutnya
yang menyatakan bahwa Upaya Administratif itu adalah Keberatan dan Banding. Hal
yang paralel juga bisa ditemui dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[8]
Berbeda dengan konsep Upaya
Administratif yang selama ini dikenal dalam praktik Peradilan Administrasi
berdasarkan UU Peratun maupun dikatakan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991, yang
tidak secara tegas menyiratkan jenis maupun hierarki serta fase Upaya
Administrasi yang harus dilakukan vide
Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menetapkan dengan jelas jenis serta berjenjangnya
Upaya Administrasi yang harus ditempuh.
[9]
Pasal 76 ayat (3) Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengadilan (Tata Usaha Negara) berwenang
untuk memeriksa gugatan yang telah menempuh upaya administrasi. Sedangkan Pasal
51 ayat (3) menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa sengketa yang telah
menempuh Upaya adminstrasi adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
[10]
Bandingkan dengan pendapat,: “Apakah
lex generalis in cassu UU AP dapat
merubah lex specialis (UU PTUN)
dengan dalih UU AP lex posterior? Apakah lex posterior generalis dapat
merubah lex prior specialis?” dalam Philipus
M. Hadjon , loc.cit. hlm. 4
[11]
Bandingkan dengan pendapat,: “Apakah
lex generalis in cassu UU AP dapat
merubah lex specialis (UU PTUN)
dengan dalih UU AP lex posterior? Apakah lex posterior generalis dapat
merubah lex prior specialis?” dalam Philipus
M. Hadjon , loc.cit. hlm. 4
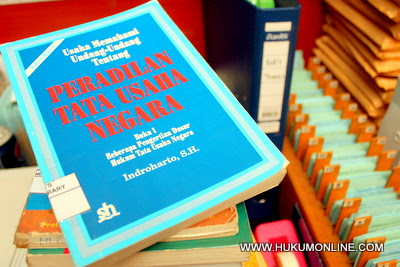
Comments
Post a Comment