(Bukan) Hakim vs Non Hakim
Bukan hendak memanaskan suasana, namun
semata-mata demi mewujudkan badan peradilan yang agung saja. Bukan hendak
membeo atau ikut-ikutan saja, tapi memang terkadang untuk memunculkan suatu isu
perlu pemantik besar sehingga menjadi perhatian publik yang pada akhirnya akan
menimbulkan ekses demi perubahan, demi perbaikan.
Menjadi berita yang cukup besar
tatkala Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun bersitegang dengan Sekretaris Mahkamah
Agung, Nurhadi di media. Persoalannya adalah lontaran keras dari Prof. Gayus
yang menyatakan bahwa Hakim Agung menjadi kelas 2 di institusinya sendiri.
Sedangkan yang menjadi kelas 1 adalah para PNS eselon I. Sontak hal tersebut
mendapat reaksi keras dan penyangkalan dari Sekretaris MA.
Agar publik tahu, di institusi
Mahkamah Agung maupun keempat lingkungan peradilan di bawahnya, ada dua golongan
besar – bila dikatakan seperti itu- yang memiliki kewenangan masing-masing.
Hakim dan non-Hakim. Ketua –Mahkamah Agung maupun Pengadilan-, merupakan Hakim
yang adalah tenaga teknis Yudisial. Sedangkan non-Hakim adalah tenaga teknis
Yudisial yakni Kepaniteraan serta Kejurusitaan, dan tenaga non teknis yakni
kesekretariatan.
Kesekretariatan memegang peranan
dominan dalam penentuan maupun pengadaan sarana dan prasarana kerja Hakim
maupun Kepaniteraan dan Kejurusitaan. Jadi dalam lingkup Mahkamah Agung, dapat
dikatakan ada 2 matahari, yakni Ketua/Wakil sebagai pimpinan serta Sekretaris
sebagai pemegang anggaran. Atau dalam lingkup Pengadilan, Ketua/Wakil sebagai
pimpinan institusi sedangkan Panitera yang merangkap Sekretaris adalah sebagai
pemegang anggaran.
Ketidaklaziman yang didobrak oleh Prof
Gayus adalah anggapan bahwa selama ini Hakim tidak perlu berkomentar hal-hal
remeh seperti itu, tidak perlu Hakim komplain soal sarana dan prasarana
kerjanya, lebih baik menggeluti perkara yang sedemikian rumit dan banyaknya.
Lebih baik menyepi dan meneliti berkas yang tak pernah habisnya, seraya
mensyukuri apa yang diterimanya sebagai sarana dan prasaran kerja.
Di tataran pengadilan tingkat pertama
maupun banding, sebenarnya hal serupa juga nyata dan ada terjadi. Terkadang
kedudukan Panitera/Sekretaris lebih dominan dalam hal penyediaan fasilitas
kerja, yang bisa berdampak pula pada kinerja hakim, bahkan martabat Hakim itu
sendiri. Bayangkan saja, salah seorang kawan Hakim pernah bercerita bahwa
Panitera/Sekretaris di tempatnya bertugas “mengkandangkan” 2 mobil dinas di Rumah
Dinasnya, sementara dia sendiri hanya naik ojek ke kantor. Di tempat lain, ada
pula PNS selevel Bendahara atau Panitera Muda yang mendapatkan jatah motor
dinas, sementara Hakim yang jelas-jelas menurut Undang-undang berhak
mendapatkan kendaraan dinas, ditawarkan kendaraan dinas pun tidak.
Dari sinyalemen di institusi Mahkamah
Agung, yang juga tercermin di banyak institusi Peradilan di bawahnya muncul
kesan, jangan-jangan selama ini bukan negara yang tidak menyejahteraan Hakim,
tapi internal Institusi Mahkamah Agung? Masih ingat tambahan anggaran Rp. 500
Milyar yang diajukan Mahkamah Agung dalam Perubahan APBN 2012? Sekretaris
Mahkamah Agung sendiri-lah yang menyatakan bahwa anggaran itu bukan untuk
peningkatan kesejahteraan hakim.
Pengajuan tambahan anggaran untuk
Mahkamah Agung, yang kemudian, yang hanya disetujui oleh DPR sekitar Rp. 405
Miliar, itu bukan untuk peningkatan kesejahteraan hakim yang dalam hal ini
adalah Tunjangan Pejabat Negara, saat gencarnya rencana mogok sidang pada saat
itu. Melainkan untuk Uang makan pegawai dan
hakim sebesar Rp. 40 miliar, tambahan tunjangan struktural sebesar Rp. 65,1
miliar serta tambahan tunjangan belanja khusus sebesar Rp. 299 miliar.
Padahal dengan penuh percaya diri saat itu beberapa anggota DPR menyatakan, itu
adalah untuk alokasi perbaikan kesejahteraan Hakim, sehingga tak perlu lagi
Hakim mengancam-ancam mogok sidang. Namun kenyataannya, sama sekali bukan
diposkan bagi tuntutan kesejahteraan Hakim.
Hal lain yang secara kasat mata dapat
dilihat adalah, dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas terkait kinerja.
PNS baik di lingkup yudisial maupun kesekretariatan, dalam satu tahun anggaran
kerap mendapat panggilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ini-itu,
sedangkan Hakim sebaliknya, bahkan ada salah seorang Hakim senior yang telah
mengabdi selama ± 5 tahun di satu Pengadilan, hanya pernah sekali mengikuti
pendidikan dan pelatihan, itu pun tentang Kode Etik & PPH, bukan persoalan
teknis yudisial. Jadi, bagaimana mungkin Hakim tidak dianaktirikan, dalam hal
peningkatan kualitas individu saja sudah diabaikan, apa lagi fasilitas untuk
menunjang kinerja yang didapatnya di kantor.
Independensi
jadi kelemahan?
Hakim yang dalam pelaksanaan
kewenangannya tak punya atasan juga tak punya bawahan, merupakan suatu
kelebihan, tapi kadang juga jadi kelemahan. PNS di lingkungan Peradilan
memiliki atasan langsung Kasubbag-nya, dan pejabat penilai atasan itu adalah
Panitera/Sekretaris. Dalam pelaksanaan kinerjanya, terkadang PNS itu lebih
tunduk dan patuh kepada Panitera/Sekretaris daripada Hakim, sehingga tugas
Pengadilan terhambat oleh itu. Padahal, sejauh itu adalah tugas yang berkaitan
dengan dinas dan fungsi yudisial harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
Hal ini secara tidak langsung kerap
jadi persoalan. Bila terjadi ketidakcocokan baik dalam persoalan kinerja maupun
pribadi antara Hakim dengan Kesekretariatan, maka amat sangat dimungkinkan
tupoksi Hakim akan menjadi terhambat hanya karena hala-hal seperti itu. Semestinya,
dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim telah diberikan fasilitas yang
lengkap, mulai hal sederhana seperti Alat Tulis Kantor (ATK) sampai hal-besar
semisal Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas. Karena meskipun tidak menjamin akan
sempurnanya tupoksi di bidang Yudisial Hakim, namun keberadaan dan kelengkapan
sarana maupun prasarana penunjang bagi Hakim akan berbanding lurus dengan
kinerjanya tersebut.
Prasangka
Bila ditelaah, sebenarnya hal tidak
fair semacam ini bertolak dari anggapan yang mengandung prasangka. Hakim
diposisikan sebagai orang yang sudah kaya dari sono-nya. Bila tidak kaya pun,
dengan jabatannya ia bisa memperkaya diri, entah dengan menerima uang suap
ataupun gratifikasi dari pihak yang bersengketa. Inilah kemudian yang menjadi
preseden, sehingga muncul anggapan bahwa, toh Hakim sudah bisa mencukupi sarana
dan prasarana kerjanya sendiri dari uang suap ataupun gratifikasi, sehingga
tidak perlu difasilitasi oleh anggaran kantor. Dan preseden yang lebih ekstrim
lagi, bila Hakim bisa mengeruk uang dari perkara yang ditanganinya, mengapa
kesekretariatan tidak boleh mengeruk keuntungan dari anggaran kantor yang
dikelolanya?
Jadi dengan adanya publikasi di media
tentang persoalan ini, hendak dibagaimanakankah Hakim? Apakah tetap
disubordinasikan oleh negara, bahkan oleh internalnya sendiri? Atau akan
dikembalikan hak-haknya secara adil dan proporsional sesuai ketentuan
perundang-undangan?
Karena sekali lagi perlu ditegaskan,
marwah dari Pengadilan adalah fungsi yudisial, fungsi mengadili, c.q. dilaksanakan oleh Hakim. sementara
fungsi-fungsi lain adalah penunjang saja. Sehingga tidak pada tempatnya Hakim sebagau
fungsi pokok mengadili, didudukkan di bawah ketiak fungsi penunjang.
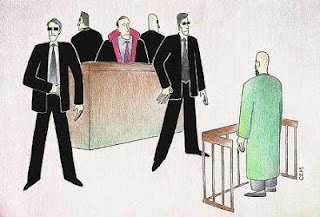
Comments
Post a Comment