PEMILU - Mozaik kecil demokrasi
Perhelatan demokrasi yang akan berlangsung dalam hitungan beberapa hari ke depan, hendaknya menjadi suatu titik tolak baru dalam sebuah perjalanan bangsa menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Setiap pihak yang berkepentingan dan terkait hendaknya menyadari bahwa tanggung jawab mewujudkan tujuan bernegara, yaitu; “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …” adalah berawal dari niat yang tulus dalam memilih dan menentukan penyambung suara rakyat di dewan perwakilan yang terhormat. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk berpartisipasi dalam hal itu, dengan tidak apatis maupun fanatis.
Perubahan konfigurasi politik dan hukum yang terjadi lebih kurang 10 tahun belakangan, merupakan angin segar bagi perubahan dan perbaikan stabilitas nasionla secara umum. Meskipun pada kenyataannya baru perubahan yang terjadi, sementara perbaikan masih sebatas angan dan impian. Peran aktif masyarakat merupakan syarat mutlak dari konsep politik “bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” yang dipakai di Indonesia. Konsep bernama demokrasi itu filosofi utamanya adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dan negara manapun di dunia yang menganut dan mengaku sebagai negara demokrasi, pastilah memuat partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemilihan umum sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegaranya.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi dan menyatakan salah satu pasal dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau dengan kata lain, menganulir dan menetapkan bahwa calon anggota legislatif yang terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak yang didapatnya. Bukan berdasarkan nomor urut calon anggota legislatif tersebut. Hal tersebut mempertegas pengakuan terhadap kedaulaan rakyat, yang sebenarnya bergema sejak Thomas Hobbes memuat konsep kedaulatan rakyat dahulu kala. Secara garis besar, ini berarti masyarakatlah yang berhak menentukan sendiri siapa-siapa saja calon wakil mereka di dewan legislatif, tidak lagi disetir dan ditentukan oleh partai politik.
Tentu pada awalnya banyak pihak yang kebakaran jenggot dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, merasa bahwa putusan tersebut mencederai konsensus awal anggota dewan di legislatif. Argumen yang diajukan pun beragam; diantaranya kekhawatiran anggota legislatif yang terpilih dari partainya, sebenarnya bukan kader partai tersebut, atau alasan klasik bahwa nantinya kompetisi politik tak hanya terjadi antar partai politik, tapi juga di dalam satu partai politik, antar calon anggota legislatifnya sendiri. Sebuah hal yang ironi, di tengah upaya sporadis untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Adalah lebih masuk akal bahwa argumen yang sebenarnya adalah ketakutan dari kelompok status quo, tersingkir dari kursi mahal nan empuknya. Selama ini, dengan senioritas dan –menurut mereka- pengalamannya di kancah politik, membuat mereka mudah melenggang ke Senayan, berapapun suara yang mereka dapat. Karena sebelum ini, nomor urutlah yang menentukan lolos tidaknya mereka menjadi anggota dewan. Jadi, meskipun perolehan suara junior mereka atau caleg dengan nomor urut lebih besar dari mereka, lebih banyak mendulang suara, yang terjadi adalah suara-suara tersebut akan dilimpahkan secara otomatis kepada nomor urut yang lebih kecil, setelah memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sudah barang tentu perubahan regulasi dari Mahkamah Konstitusi ini membuat mereka tidak bisa lagi bersantai-santai atau tidur pulas. Kelompok status quo, yang memang mapan dan telah lama duduk di dewan perwakilan, kini harus pula berpayah-payah seperti para politikus kacangan-juniornya-, agar mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dan memenuhi BPP itu, sehingga tujuan akhir mereka, yaitu tertidur pulas di kursi empuk nan mahal di Senayan pun kembali terwujud.
Seperti halnya kelompok status quo yang cukup merasa kebingungan dengan perubahan regulasi itu, masyarakat Indonesia pun akan semakin dipusingkan dengan begitu banyaknya pilihan dalam pemilu kali ini. Tak cukup dengan jumlah partai yang lebih banyak dari pemilu tahun 2004, kini kepala mereka pun akan lebih pening dengan rentetan calon legislatif yang akan mereka pilih pada 9 April mendatang. Ya, genderang “perang pribadi” calon anggota legislatif pun muncul selepas constitutional review terhadap Undang-undang Pemilu tersebut. Para calon anggota legislatif mulai berkampanye secara pribadi, selain mengusung partai politik, juga mempromosikan nomor urutnya dalam partai politik itu. Sehingga kompetisi politik pun semakin panas, ketat, namun fair dan makin membingungkan. Terlebih ada pula perubahan tata cara pemilihan, dari mencoblos menjadi mencontreng. Dan masyarakat Indonesia kembali bingung, setelah naik-turunnya (dan kemungkinan naik lagi) harga BBM, kelangkaannya, berbagai bencana, serta kelakuan elit politik yang mirip badut yang menggemaskan, ditambah dengan berbagai perubahan regulasi pemilu, yang dijamin tidak akan mudah diterima dan dipahami masyarakat marginal. Kita lihat saja nanti pada saat pelaksanaannya, apakah masyarakat mengerti tentang perubahan itu, ataukah masih menyangka regulasinya sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar dan sesuai rencana.
Adanya revisi terhadap regulasi tentang penentuan calon anggota legislatif terpilih itu, menutup salah satu pintu–dari cukup banyak- kelemahan demokrasi, yaitu kepraktisan dan proses instan. Dua hal ini dapat diartikan secara bebas menjadi “tidak perlu bekerja keras, karena hasilnya sudah dapat diraih sebelum bekerja”, begitulah kira-kira stigma yang terbentuk selama ini, dan–untungnya- dihapuskan oleh Institusi penguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang dibentuk tahun 2004 tersebut. Parahnya, karakteristik ingin mencapai keinginan secara praktis dan proses yang instan tersebut, tak hanya dimonopoli oleh status quo yang menolak perubahan regulasi tentang nomor urut itu. Masyarakat kita pada umumnya – bahkan mungkin termasuk penulis sendiri- juga berkarakter seperti itu.
Pembenaran dan pemakluman atas hal itu adalah fakta bahwa bangsa Indonesia sudah terlalu lama dibodohi. Akibat 3,5 abad dijajah Belanda; 3,5 tahun dikibuli Jepang, dan lebih dari 3 dekade dikekang dan dibuai mimpi-mimpi dangkal, membuat pikiran kita makin bebal. Maka setelah itu sepertinya hanya ada satu pilihan pahit, melanjutkan pembodohan dan pembohongan ini sampai kita merasa muak sendiri. Agak sarkastik memang, namun bila diibaratkan, bangsa Indonesia adalah seperti orang yang kelaparan akibat 7 hari 7 malam tidak makan, lalu disuguhi berbagai macam makanan enak di atas meja. Bisa ditebak kemudian, segala macam makanan disuapkan ke mulutnya, tangan kanan memegang makanan A, yang kiri menggapai makanan B, lalu sudut matanya melihat makanan yang lebih enak, diraihnya juga. Tak puas sampai disana, di ujung meja ada pula makanan kesukaannya, diraihnya pula makanan itu. Jelas, yang terlihat hanya kekacauan. Rasa makanan tidak jelas, meja berantakan, mulut belepotan, perut kekenyangan.
Fenomena pesta demokrasi bernama pemilu di negara ini tak akan jauh dari beberapa hal rutin. Janji-janji politik, musik dangdut plus goyangan maut para penyanyinya yang semlohai, pembagian sandang-pangan, konvoi kendaraan yang menyengsarakan dan membuat gusar orang lain, janji-janji perubahan, bakti sosial dengan memakai baju partai, janji-janji perbaikan, menjelek-jelekkan lawan politik, membagikan uang pengganti bensin dan janji-janji yang membumbung tinggi. Sangat menarik bukan? Itulah apa yang ada di hadapan kita, semuanya nyata dan merupakan ritual wajib menjelang pemilu.
Hal itu didukung oleh karakter sebagian besar masyarakat Indonesia yang mungkin memang gampang dibodohi. Seperti yang telah disebutkan tadi, sifat praktis dan instan yang menguasai kepala dan perut masyarakat Indonesia lebih banyak menyebabkan kemudharatan. Lumrah bila kita temui dalam setiap menjelang pemilu, kompensasi yang diminta oleh masyarakat harus bisa dirasakan secara langsung oleh mereka. Entah itu pembagian uang 10-50 ribu per kepalanya, atau bantuan lain seperti penyediaan fasilitas olahraga seperti bola voli, bola sepak, net dan sebagainya oleh para calon anggota legislatif, yang sering diminta oleh para pemuda atau kelompok pemuda. Dan itulah kenyataan yang ada, masyarakat kita sudah hafal di luar kepala dengan janji-janji, program-program usang yang mereka anggap tak pernah menyentuh kepentingan mereka. Peduli apa mereka dengan pengentasan kemiskinan, pembebasan sekolah dari biaya, subsidi tetek-bengek, perluasan lapangan kerja, yang penting ada kompensasi langsung terhadap suara yang mereka berikan. Momen pemilihan umum tidak hanya dimanfaatkan oleh para calon anggota legislatif, tapi juga oleh para oportunis yang memanfaatkannya dengan “meminta-minta” kepada para calon itu sebagai kompensasi dipilihnya mereka kelak.
Ironisnya apa yang didapat sebagian masyarakat itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang mereka tuai di kemudian hari, atau lebih tepatnya apa yang para calon legislatif terpilih itu tuai di kemudian hari. Bila para pemuda memilih karena diberi bola voli, atau bola sepak saja, yang akan didapat anggota legislatif perbulan beratus kali lipat dari harga bola itu. Apa yang didapat per kepala sebesar 50 ribu rupiah, akan sangat jomplang bila para caleg yang terpilih itu kelak melakukan korupsi beratus-ratus miliar rupiah. Apa kita rela mendapatkan uang 50 ribu rupiah, namun kemudian kita “kecurian” uang 500 miliar rupiah? Meski kita cenderung apatis dan tidak merasakan secara langsung efek korupsi tersebut, namun sebenarnya akibat itu ada di depan mata kita. Harga minyak nasional yang tidak stabil, harga sembako yang senang bermain-main di atas kepala, biaya pendidikan yang seharga 5 tahun menggadaikan sawah, atau yang paling jelas dan terkini adalah bencana Situ Gintung akibat anggaran pemeliharaan yang menguap entah kemana, dengan kompensasi 100 orang masyarakat meninggal. Bukankah itu akibat nyata dari korupsi yang tidak terlihat dan laten terjadinya?
Demokrasi apapun bentuknya adalah sebuah pilihan yang sudah diambil para pendiri negara kita. Dengan segala baik buruknya, itu tetap harus dijunjung tinggi. Politik representasi semacam pemilihan umum tak lepas dari berbagai kelemahan. Dan yang paling pasti dalam demokrasi adalah, tidak ada sebuah kebenaran. Yang ada hanyalah pembenaran. Ketika kehendak mayoritas menentukan benar, itulah kebenaran. Tak peduli sebenarnya kaum minoritaslah yang benar. Ketika suara terbanyak memilih sebuah kebenaran, berarti sisa dari itu adalah tidak benar. Baik-buruk adalah relatif, tapi menang dan kalah adalah pasti dalam demokrasi. Tak hanya dari konsep representasi, pemerintahan dan nilai kebenaran, konsep hukum pun sangat relatif bila dihadapkan pada demokrasi. Sangat kompromistis dan berubah-ubah.
Hingga dari hitungan hari yang tersisa, adalah peran aktif kita untuk menjadi bagian dan memilih sendiri kebenaran itu. Adalah peran aktif kita membentuk secara sistematis dan berkesinambungan suatu kebenaran yang memang benar. Bukan kebenaran yang dipaksakan, atau kebenaran mayoritas. Pastikan bahwa yang kita pilih nanti, -apapun dan siapapun itu- merupakan representasi dari keyakinan kita dengan disertai alasan yang masuk akal dan obyektif, tentang seorang wakil rakyat yang kredibel, kapabel dan memegang teguh kebenaran, seperti yang kita idamkan. Yakini bahwa yang kita lakukan adalah benar, jangan terbutakan oleh rentetan gelar, kharisma pribadi, klaim-klaim kesuksesan yang dangkal dan sebagainya. Orang-orang benarlah yang kita cari, bukan orang-orang betul. Karena yang hadir dari orang-orang benar adalah kebenaran, sedang yang lahir dari orang-orang betul adalah kebetulan.
Buka mata selebar-lebarnya, cari informasi sebanyak-banyaknya, tentang apa dan siapa yang kita pilih. Sehingga demokrasi yang ideal –menurut sebagian orang- akan bisa menghasilkan sebuah harapan dan pencapaian baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan pemilu akan benar-benar menjadi sebuah perayaan dan kegembiraan bangsa Indonesia, hajat besar bangsa Indonesia. Bukannya "buang" hajat besar bangsa Indonesia.
Majalengka, 2 April 2008
Cag ah,
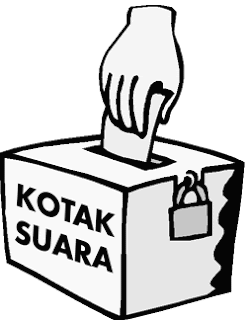
Comments
Post a Comment